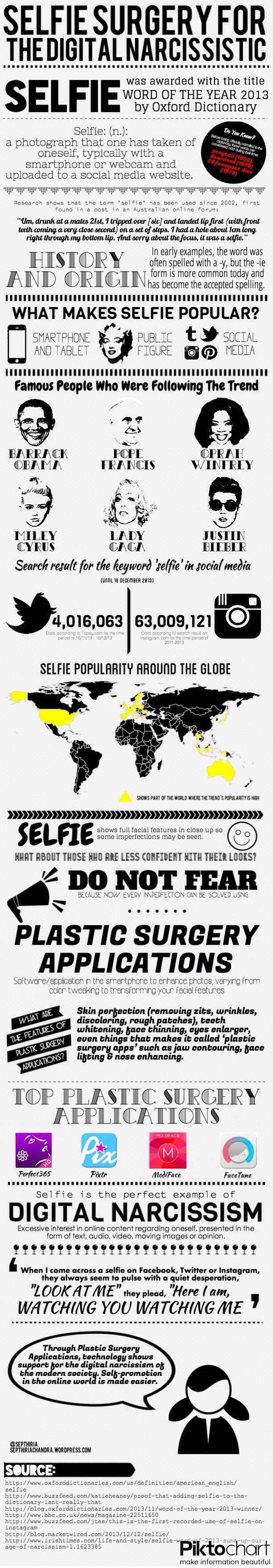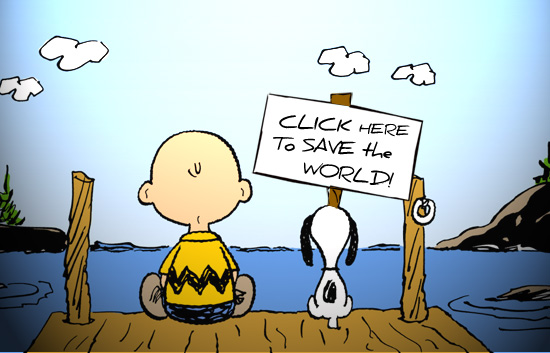Seberapa banyak dari kalian yang pernah menandatangani petisi online di situs-situs seperti change.org atau kickstarter.com? Mungkin membantu menyebarkan suatu isu di media sosial melalui retweet dan link sharing? Atau yang paling populer belakangan ini, menyumbangkan like pada fanpage suatu akun gerakan sosial atau foto yang berjanji akan melakukan amal apabila mencapai sejumlah angka likes? Bagi kalian yang pernah melakukan hal-hal tersebut, Anda dapat mengaku sebagai seorang aktivis dunia maya, atau yang dikenal dengan sebutan clicktivist.
Portmanteau dari kata click dan activist ini mengacu pada mereka yang melakukan aksi-aksi sosial melalui dunia maya – dengan meng-klik – untuk cause apapun. Menurut Oxford Dictionary, clicktivist berarti:
“The use of social media and other online methods to promote a cause.”
Penggunaan media sosial untuk penyebaran dan sosialisasi suatu isu memang terbukti mampu menggapai cakupan yang lebih luas dibandingkan media konvensional. Melalui media sosial, suatu isu dapat lebih cepat tersebar dan menyentuh lebih banyak orang. Namun pada perkembangannya, para aktor yang berperan dalam clicktivism ini mengalami pergeseran menjadi sesuatu yang dikenal dengan istilah slacktivism.
Berbeda dengan clicktivist yang secara sadar mendukung suatu gerakan sosial, para slacktivist memiliki kecenderungan untuk ikut-ikutan gerakan sosial apapun tanpa memahami apa yang mereka dukung. Contoh paling gampang ditemui adalah ajakan untuk meng-klik like pada suatu gambar atau akun suatu gerakan sosial seperti yang disebutkan diatas.
Gerakan slacktivism menjadi marak karena sifatnya yang low-commitment. Dengan menyumbangkan satu like, seseorang dapat merasa telah melakukan sumbangsih terhadap suatu gerakan sosial tanpa sebenarnya berbuat apa-apa.
“Slacktivism shows that young people in particular are happy to support a fashionable aim or cause when it doesn’t take much effort to do so.” – Metro UK
Padahal, jumlah like pada dasarnya tidak membantu pelaksanaan gerakan sosial selain membantu menyebarkannya. Gerakan sosial tetap membutuhkan sejumlah uang yang harus dicapai untuk dapat benar-benar berdampak pada masyarakat. Gawatnya, sifat para slacktivist yang hanya berpartisipasi memberikan like dianggap berpotensi menurunkan jumlah donasi karena mereka merasa telah berkontribusi tanpa benar-benar menyadari apa yang dibutuhkan oleh gerakan sosial tersebut. Dengan demikian, gerakan sosial hanya akan tersebar tanpa benar-benar mencapai tujuan utamanya. Hal inilah yang harus disadari oleh setiap orang yang berpartisipasi di gerakan sosial online karena; “Clicking likes don’t save lives. Money does.” – Unicef.
Septhiria.